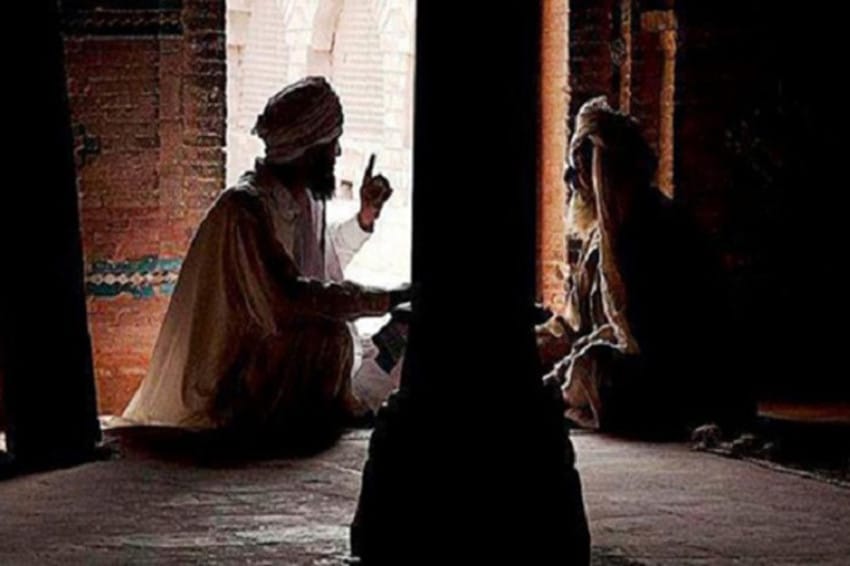Dalam wacana pemikiran Islam, khususnya yang menyentuh kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad, istilah imamah dan khilafah kerap menjadi pusat diskusi dan perbedaan penafsiran. Ketidakjelasan dalam memahami nuansa makna kedua istilah ini telah memicu perdebatan panjang yang menguras energi intelektual dan sosial dalam upaya mencari titik temu. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih tegas, mendalam, dan distingtif terhadap imamah dalam tradisi Syiah dan khilafah dalam tradisi Sunni menjadi sangat penting.
Dalam pandangan Syiah, imamah adalah kepemimpinan yang berakar pada ketetapan ilahi (nash) dan penunjukan langsung dari Allah melalui Nabi Muhammad. Ia memiliki karakter sakral dan transenden, di mana otoritasnya adalah mandat spiritual dan keagamaan yang melampaui kesepakatan manusia semata. Dengan demikian, imamah lebih tepat dipahami sebagai kewenangan (dalam arti authority), sebuah legitimasi yang bersumber dari dimensi ilahi, kepercayaan, dan mandat dari Sang Pencipta. Kewenangan ini merepresentasikan ajaran agama yang otentik dan menjadi rujukan definitif bagi umat.
Sebaliknya, kekhalifahan, sebagaimana dipahami oleh mayoritas Sunni, adalah kepemimpinan yang lahir melalui konsensus (ijma’) atau perjanjian (bai’ah), meskipun implementasinya dalam sejarah Islam pasca-Nabi tidak selalu konsisten. Otoritas dalam kekhalifahan lebih bersifat teknis dan administratif, yaitu kekuasaan yang mengelola masyarakat dalam wilayah teritorial formal. Karena itu, kekhalifahan lebih tepat dimaknai sebagai kekuasaan aktual yang bersifat kondisional.
Kekuasaan profan ini dalam sejarah dikukuhkan melalui berbagai cara, seperti: kesepakatan perwakilan terbatas (ahl al-halli wa al-‘aqd) dalam pemilihan Abu Bakar, penunjukan langsung oleh penguasa sebelumnya (istikhlaf) seperti penunjukan Umar oleh Abu Bakar, penunjukan oleh elit terbatas dalam rapat tertutup untuk Utsman, pengakuan atas dasar prioritas religio-politik terhadap Ali yang diangkat oleh mayoritas masyarakat Madinah, hingga pengambilalihan kekuasaan secara paksa (coup d’état) seperti yang dilakukan Muawiyah terhadap Ali, yang kemudian meletakkan dasar bagi kekhalifahan dinasti (khilāfah ‘ala al-manhaj al-sulālah) yang terinstitusionalisasi pada masa Umayyah, Abbasiyah, dan mencapai puncaknya pada monarki Kesultanan Utsmaniyah.
Peralihan kekuasaan secara turun-temurun ini menegaskan bahwa kekhalifahan dalam praktiknya lebih merupakan struktur politik duniawi yang adaptif terhadap realitas sosio-historis, bukan sistem sakral yang kaku seperti yang sering diidealkan. Istilah ini merujuk pada kekuasaan de facto yang mapan demi menegakkan hukum, melanggengkan status quo, dan mengatur tatanan sosial serta ekspansi, sebagaimana tercermin dalam catatan sejarah.
Perbedaan mendasar antara kewenangan (imamah) dan kekuasaan (khilafah) terletak pada sumber legitimasi, cakupan fungsi, sifat aktualisasi, dan fokus utama. Kewenangan dalam imamah mendapatkan legitimasinya langsung dari ketetapan ilahi (divine legitimacy), sebuah pengakuan dan pembenaran yang berasal dari dimensi spiritual dan teologis. Ia adalah hak dan tanggung jawab yang dianugerahkan oleh Allah kepada individu-individu terpilih. Sedengkan kekuasaan dalam khilafah mendapatkan legitimasinya dari akseptabilitas publik (public acceptability), sebuah pengakuan dan dukungan yang berasal dari mayoritas umat melalui mekanisme konsensus, pemilihan, atau cara lainnya.
Kewenangan (imamah) bersifat potensial dan normatif. Ia adalah kapasitas atau hak yang melekat pada individu-individu yang telah ditetapkan secara ilahi, terlepas dari apakah mereka secara faktual memegang tampuk pemerintahan atau tidak. Esensi imamah terletak pada legitimasi dan kapasitas spiritual serta intelektual yang dimiliki oleh para Imam, bahkan ketika mereka tidak memiliki kekuasaan politik formal.
Sebaliknya, kekuasaan (khilafah) bersifat aktual dan operasional. Ia adalah kemampuan yang terwujud dalam tindakan nyata untuk memerintah, mengelola sumber daya, dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Eksistensi khilafah sangat bergantung pada adanya struktur pemerintahan yang berfungsi dan pengakuan dari mayoritas umat atau dukungan elit politik yang kuat.
Konsep khilafah dalam tradisi Sunni menghadapi paradoks legitimasi yang kompleks:
1. Dilema Akseptabilitas Publik: Secara teoritis, khilafah digambarkan sebagai kekuasaan yang sah melalui ijma’ (konsensus) atau bai’ah (sumpah setia). Namun, dalam sejarah, proses ini seringkali elitis (pemilihan Abu Bakar oleh ahl al-halli wa al-‘aqd) atau bahkan koersif (kudeta Muawiyah). Klaim legitimasi dari "penerimaan publik" menjadi rapuh jika masyarakat tidak berpartisipasi aktif atau menolak kepemimpinan tersebut (misalnya, non-Muslim atau minoritas Syiah di bawah Umayyah). Akibatnya, khilafah lebih mengandalkan kontrol teritorial dan stabilitas politik daripada legitimasi partisipatif.
2. Dilema Teologis: Jika khilafah dijustifikasi sebagai "kewajiban agama" (seperti klaim kelompok Islamis kontemporer), ia berbenturan dengan konsep imamah dalam Syiah yang merupakan sistem teokratis berbasis nash (ketetapan ilahi). Klaim teologis ini mengaburkan esensi khilafah sebagai sistem politik duniawi, bahkan memunculkan upaya legitimacy laundering dengan mencampuradukkan otoritas vertikal yang sakral dan kekuasaan administratif yang profan (misalnya, klaim penunjukan khalifah pertama melalui isyarat implisit Nabi).
Akibatnya, khilafah kehilangan kekhasannya sebagai model kepemimpinan kondisional dan terjebak dalam ambiguitas antara "kewenangan vertikal," "kepemimpinan sakral" (seperti imamah), dan "pemerintahan profan."
Ambiguitas khilafah bersumber dari:
1. Ketidakjelasan Batasan Teologis: Sunni tidak memiliki doktrin yang rigit tentang bentuk negara. Khilafah adalah temuan historis, bukan konsep yang terdefinisi rinci dalam Al-Qur’an atau Hadis. Istilah "khalifah" sendiri ambigu, apakah berarti "pengganti Nabi" (dalam urusan politik) atau "wakil Allah" (dalam urusan spiritual)? Perbedaan interpretasi ini memungkinkan kekuasaan sekuler mengklaim legitimasi agama, seperti gelar "Khalifah" yang digunakan Dinasti Utsmaniyah setelah runtuhnya Abbasiyah.
2. Kekuasaan vs. Kewenangan : Dalam praktiknya, khilafah lebih sering menjadi alat legitimasi kekuasaan dinasti daripada perwujudan ideal kepemimpinan Islam. Contohnya, monarki Turki Utsmani menggunakan simbol khilafah untuk menguasai wilayah multi-etnis dan multi-agama. Upaya menggabungkan legitimasi teologis ("hak ilahi raja") dengan akseptabilitas publik ("kontrak sosial") menciptakan kontradiksi internal. Khilafah tidak sepenuhnya sakral seperti imamah, tetapi juga tidak sepenuhnya sekuler seperti negara modern.
Agar tetap bermakna dan relevan, khilafah perlu dipahami dalam dua kerangka terpisah:
1. Sebagai Konsep Historis: Khilafah adalah sistem politik klasik yang lahir dari konteks sosio-kultural abad pertengahan, dengan segala kelemahannya (nepotisme, militerisme, marginalisasi minoritas). Contohnya, kebijakan menetapkan wilayah masyarakat yang enggan membayar pajak sebagai zona kemurtadan atau kebijakan pajak (kharaj) di era Umayyah-Abbasiyah yang lebih mencerminkan logika fiskal kekaisaran daripada prinsip keadilan Islam.
2. Sebagai Simbol Retoris: Dalam wacana kontemporer, khilafah sering digunakan sebagai alat mobilisasi politik oleh kelompok Islamis, bukan sebagai model yang koheren. Klaim "kembali ke khilafah" mengabaikan kompleksitas sejarah dan pluralitas masyarakat modern.
Dalam ranah fungsi, kewenangan (imamah) memiliki fokus utama pada supervisi spiritual dan pengarahan ideologis. Para Imam dalam tradisi Syiah dipandang sebagai penjaga ajaran Islam yang autentik, penafsir wahyu yang benar, dan pembimbing moral bagi umat, bahkan bagi umat Islam di luar komunitas Syiah. Fungsi mereka adalah memberikan visi spiritual, prinsip-prinsip etika, dan kerangka nilai sebagai landasan kehidupan beragama.
Sementara itu, kekuasaan (khilafah) memiliki fokus utama pada pengelolaan urusan teknis pemerintahan.
Dengan pembedaan yang lebih tajam antara pengertian, sumber legitimasi, sifat aktualisasi, dan fokus fungsi kewenangan (imamah) dan kekuasaan (khilafah), kita dapat melihat bahwa keduanya tidak harus saling bertentangan atau meniadakan. Justru, relasi keduanya dapat dipahami sebagai sebuah irisan. Idealnya, seorang pemimpin umat dapat memiliki baik kewenangan spiritual dan intelektual yang diakui secara teologis, maupun kekuasaan politik yang didukung oleh akseptabilitas publik.
Contoh konkret yang sering menjadi titik temu kedua konsep ini adalah figur Ali bin Abi Thalib. Bagi mayoritas Syiah, Ali adalah Imam pertama yang memiliki kewenangan spiritual dan legitimasi ilahi yang secara eksplisit ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Di sisi lain, bagi mayoritas Sunni, Ali adalah khalifah keempat yang memegang kekuasaan setelah melalui proses konsensus dan penerimaan oleh sebagian besar umat pada masanya. Dalam diri Ali, kedua dimensi kepemimpinan ini—legitimasi teologis dan akseptabilitas publik—bertemu.
Implikasi dari pemahaman ini adalah bahwa doktrin imamah (konsep kepemimpinan menurut perspektif Syiah), yang menekankan pada kewenangan yang bersumber dari divine legitimacy dan kapasitas spiritual, tidak secara inheren mendelegitimasi konsep khilafah (konsep kepemimpinan menurut perspektif Sunni), yang menekankan pada kekuasaan yang berlandaskan akseptabilitas publik dan pengelolaan urusan duniawi. Sebaliknya, kedua konsep ini dapat dipandang sebagai dua sisi mata uang yang sama dalam memahami kompleksitas kepemimpinan umat Islam. Kepemimpinan yang ideal mungkin justru terwujud ketika seorang pemimpin memiliki baik legitimasi spiritual dan intelektual yang kuat, maupun dukungan dan kepercayaan dari umat yang dipimpin.
Pemahaman yang lebih mendalam terhadap perbedaan dan potensi irisan antara imamah dan khilafah membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif, mengurangi potensi konflik sektarian, dan memungkinkan umat Islam untuk menyadari bahwa ketegangan selama berabad-abad boleh jadi adalah akibat kesalahpahaman mutual dan kecenderungan memperkuat perbedaan demi mempertahankan identitas sektarian.
Akhirnya, umat Islam Sunni dan Syiah bisa move on dari dendam masa lalu yang dipelihara oleh pihak luar dan dianggap sebagai alasan untuk saling menyesatkan oleh segelintir orang yang tidak bijak di kedua kelompok. Setidaknya, kedua peradaban agung ini bertemu dalam sosok yang diyakini sejak awal sebagai imam dan kemudian dipilih sebagai khalifah. Beliau adalah keluarga Nabi sekaligus sahabat Nabi. Beliau adalah Ali.
http://t.me/ArsipChannel_Tulisan_ML